Oleh: Sri Widayati
A. Pendahuluan
Sastra cyber sudah muncul beberapa
tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 2001. Kehadirannya ditengarai dengan terbitnya buku Graffiti
Gratitude pada tanggal 9 Mei 2001. Graffiti Gratitude merupakan buku antalogi puisi cyber.
Penerbitan antalogi tersebut dimotori oleh Sutan Iwan Soekri Munaf, Nanang
Suryadi, Nunuk Suraja, Tulus Widjarnako, Cunong, dan Medy Loekito. Mereka
tergabung dalam satu yayasan yaitu Yayasan Multimedia Sastra (YMS).
Kemunculan sastra cyber dalam kancah
kesusasteraan Indonesia ditanggapi dan diapresiasi secara berbeda-beda. Bahkan,
hal ini sempat menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Di satu pihak ada
yang menyambut secara positif, tetapi di pihak lain ada yang menyambutnya
secara negatif. Disambut secara positif karena kehadiran sastra cyber dapat dengan
mudah dan cepat diakses oleh kalangan yang lebih luas, tidak hanya di Indonesia,
tetapi juga di seluruh dunia. Selain itu, kehadiran sastra cyber melalui media
internet memberi peluang bagi penulis yang bergiat di bidang sastra untuk
memberikan sumbangsihnya, baik berupa
karya maupun pemikiran-pemikiran, tanggapan-tanggapan terhadap karya sastra.
Disambut negatif karena sastra cyber dianggap tidak lebih dari sekadar upaya
main-main saja. Sastra ini juga dikatakan sebagai sastra yang kualitasnya
sangat kurang. dan tidak memberikan kemajuan yang berarti dalam khasanah
kesusasteraan Indonesia.
Lepas dari persoalan di atas,
sebenarnya berkembangnya teknologi, mau tidak mau akan berpengaruh besar
terhadap budaya suatu bangsa, tidak terkecuali sastra. Tentunya berkembangnya teknologi di satu sisi
akan berdampak positif dan di sisi lain akan membawa dampak yang negatif.
Begitu juga terhadap kehadiran sastra melalui media elektronik. Namun, tentu
saja kita tidak perlu merisaukan sastra cyber yang kata sebagian pemerhati sastra ditulis ’semau
gue’ karena bagaimanapun juga sastra yang demikian akan tereleminasi dengan sendirinya.
Dengan kata lain, waktu yang akan menentukan, apakah karya-karya tersebut akan
tetap eksis atau tidak.
Hadirnya
sastra cyber melalui media elektronik sebaiknya jangan dipandang sebelah
mata. Bagaimanapun juga tidak adil jika
semua karya yang ditulis melalui media tersebut diklaim sebagai tulisan yang tidak bermutu.
Seharusnya, sastra cyber tetap dapat
diterima secara positif karena mau tidak mau, sastra tersebut akan ikut
menentukan perkembangan sastra Indonesia. Melalui media elektronik diharapkan paling
tidak untuk ke depannya akan memunculkan banyak kemungkinan baru yang dilakukan
oleh para penulis. Dikatakan oleh Suryadi (dalam Situmorang, 2004:9) bahwa jika
selama ini para sastrawan hanya menampilkan karyanya pada buku, majalah,
koran—yang berwujud kertas—maka saat ini ditemukan karya-karya mereka yang
tersebar di media internet. Sebuah media maya yang menghubungkan satu komputer
dengan berjuta-juta komputer lainnya.
Hadirnya internet sebagai media
sastra cyber tentu mengundang tanya, akankah eksistensi sastra cyber akan
diakui dalam sejarah sastra? Akankah ia dicatat
sebagai bagian dari sejarah sastra Indonesia? Untuk hal tersebut akan
dilihat bagaimana komentar-komentar para pemerhati sastra. Namun, sebelum itu
akan diuraikan secara sekilas tentang cyber sastra.
B. Cyber Sastra
Cyber dapat diartikan ’maya’, sastra cyber atau cyber sastra merupakan
sastra yang lahir sebagai dampak
perkembangan teknologi. Jika sastra sebelumnya menggunakan koran dan
majalah sebagai mediumnya, sastra cyber mediumnya elektronik (internet).
Dibandingkan sastra koran atau
majalah, dalam sastra cyber, penulis
mengalami kemudahan di dalam pemunculan karyanya di hadapan pembaca karena
tidak ada seleksi yang ketat terhadap sastra tersebut. Oleh karena itu,
kemungkinan besar medium elektronik sebagai sarana pengungkapan ekspresi
seseorang akan mengalahkan dan menggeser medium yang ada sebelumnya. Semua itu terjadi karena pesatnya perkembangan
teknologi.
Berkembangnya
teknologi terutama internet dapat dikatakan sebagai sebuah revolusi yang besar
pengaruhnya dalam kehidupan ini. Salah satu pengaruhnya adalah terhadap dunia
sastra. Seperti telah kita ketahui bahwa
sastra merupakan bagian dari kebudayaan
suatu bangsa. Kebudayaan suatu bangsa tentu akan mudah berkembang, seiring dengan berkembangnya teknologi. Dengan adanya
internet, paling tidak dapat dimanfaatkan untuk membantu perkembangan sastra
dengan lebih baik.Internet dengan sendirinya memberi ruang baru bagi seseorang
untuk berkarya. Sebelum media ini muncul, koran dan majalah adalah media yang
digunakan penulis untuk menyalurkan bakat atau hobinya. Namun, terbatasnya
ruang dalam media tersebut dapat
dikatakan tidak banyak membantu perkembangan sastra dengan baik.
Kecanggihan komputer dan ketinggian
daya kreatif memberikan hasil yang luar biasa, tidak terkecuali sastra. Sastra
cyber tentunya akan memiliki
prospek yang semakin cerah tidak saja di
Indonesia, tetapi juga di belahan dunia yang lain. Sastra cyber memberikan
kesempatan yang luas, tidak saja bagi penulis untuk menulis karya sastra,
tetapi juga pada pembaca untuk melakukan apresiasi sastra secara leluasa. Namun, kehadirannya
telah membawa polemik yang cukup ramai. Hal tersebut disebabkan masih ada yang
membedakan sastra dari segi medianya. Ada sastra majalah, koran, dan cyber.
Sastra majalah dan koran dianggap lebih baik atau lebih tinggi mutunya daripada
sastra cyber. Hal ini disebabkan sebuah karya yang terbit dalam kedua media
tersebut harus melewati seleksi yang ketat. Berbeda dengan sastra cyber, yang
tidak melewati seleksi yang ketat seperti yang tampak pada kedua media
tersebut. Selain masalah media yang diperdebatkan, juga anggapan adanya
hegemoni para senior yang tidak menginginkan eksistensinya dilanggar oleh
penulis yunior. Oleh karena itu, berikut akan ditampilkan polemik yang muncul berkaitan dengan hadirnya sastra cyber.
Polemik
Sekitar Sastra Cyber
Tidak sedikit pandangan dan komentar
yang dilontarkan para pemerhati sastra terhadap kehadiran sastra cyber di
Indonesia. Seperti dikemukakan di atas, bahwa ada yang menanggapi secara
positif maupun negatif terhadap sastra
cyber. Berikut akan ditampilkan
pandangan sekitar sastra cyber.
Dikatakan oleh Ahmadun Yosi Herfanda
(redaktur koran Republika) dalam salah artikel yang dimuat dalam Republika dengan judul ”Puisi Cyber, Genre
atau Tong Sampah”. Dalam artikel tersebut Ahmadun mengatakan bahwa sastra yang dituangkan melalui media cyber cenderung
hanyalah sebagai ”tong sampah.” Dikatakan demikian, karena menurutnya sastra
cyber merupakan karya-karya yang tidak
tertampung atau ditolak oleh media sastra cetak (2001). Lebih lanjut dikatakan bahwa media cyber membuka ruang yang luas bagi
tumbuhnya sastra alternatif yang ”memberontak” terhadap kemapanan – terhadap
estetika yang lazim—dan bukan hanya menjadi media duplikasi dari tradisi sastra
cetak. Sebab di sanalah tempat bagi semangat dan kebebasan kreatif, yang
seliar-liarnya sekalipun, yang selama ini tidak mendapat tempat selayaknya di
media sastra cetak, baik di rubrik sastra koran, majalah sastra, maupun
antalogi sastra.
Selanjutnya Sutarji Coulsoum Bachri (dalam
Efendi, 2004:90) yang dikenal sebagai presiden ”Penyair Indonesia” mengatakan dengan
cukup pedas bahwa ’tai yang dikemas secara menarik akan lebih laku dibandingkan
dengan puisi yang dikemas secara asal-asalan’. Pernyataan ini dilontarkan
berkaitan dengan cover yang tampak pada buku antalogi sastra cyber yaitu Graffiti
Gratitude yang dipandang kurang baik sehingga buku itu tidak layak untuk
dijual.
Masih berkaitan dengan sastra cyber,
Maman S. Mahayana (dalam Situmorang, 2004:62) menyatakan bahwa kualitas
penyair-penyair cyber masih dipertanyakan, sebagian masih tergolong sebagai
penulis yang baik, belum sebagai penyair. Kemudian Juniarso
Ridwan, seorang penyair dari Bandung, (dalam Situmorang, 2004:255) menanggapi pernik-pernik
yang tampak pada sastra cyber seperti background,
backsound, dan variasi yang terdapat pada kata-kata. Ia mengatakan bahwa apa artinya loncatan-loncatan
huruf, selain memperlihatkan kecanggihan teknologi digital. Apa pengaruhnya
suara-suara musik yang secara esensial tidak terkait dengan teks yang muncul,
selain hanya untuk konsumsi telinga yang secara historis-biologis sulit untuk
melakukan korespondensi makna.
Berkaitan dengan pernyataan Ahmadun, Sutarji
Coulsoum Bachri, Maman S. Mahayana, dan Juniarso Ridwan di atas timbul reaksi
dari berbagai pihak, antara lain dari Sutan Iwan Soekri Munaf (2004:95). Ia mengatakan bahwa penilaian yang dilakukan Ahmadun adalah penilaian yang terburu-buru.
Ahmadun hanya memberikan sampel yang terbatas dan rentang waktu yang pendek sehingga
perlu dipertanyakan kesahihan penilaian itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa
sebagai sarana, dunia cyber pada akhirnya sebagaimana alam nyata, akan
memberikan ujian tersendiri bagi penyair maupun sastrawan. Hanya penyair dan
sastrawan teruji di dunia cyber yang akan menghasilkan karya ”berbunyi”. Tentu
saja ”berbunyi” di sini mempunyai batasan sendiri yang disepakati masyarakat
dunia cyber.
Medy Loekito, seorang penyair
yang sekaligus presiden Yayasan
Muktimedia Sastra, (dalam Efendi, 2004:278) mengatakan bahwa perdebatan
mengenai sastra koran melawan sastra cyber adalah sesuatu yang tidak perlu. Dia
mempertanyakan bagaimana sastra koran merasa atau didudukan sebagai dewa sastra, dan
bagaimana sastra cyber dianggap sebagai sastra sampah? Adalah suatu
perbincangan yang mengada-ada, kecuali apabila perbincangan antara kedua mazhab
tersebut lebih diarahkan pada riset, studi perbandingan, dan analisis, guna
mencari jalan untuk pencapaian yng lebih maksimal.
Asep Sambodja dalam Efendi
(2008:164) berpendapat bahwa meskipun sastra cyber dicap sebagai ”Anak Haram”,
ataupun ”Tong Sampah”dalam sastra Indonesia, sastra cyber tetap memiliki hak
hidup yang sama dengan sastra lainnya. Dikatakan lebih lanjut bahwa kehidupan
sastra Indonesia masih terbelenggu dalam kanonisasi, masih tergantung pada kata
pemegang otoritas. Pemegang otoritas sastra Indonesia pertama di Indonesia
adalah pemerintah kolonial Belanda yang pada awalnya membentuk Komisi Bacaan
Rakyat yang kemudian diubah namanya menjadi Balai Pustaka. Balai Pustaka sebagai milik Belanda dan
sebagai pemegang otoritas berjalan dalam kurun yang cukup lama yaitu hampir
satu abad sejak tahun 1900. Sambodja (dalam Efendi, 2008:165) mengatakan, apa
yang terjadi pada masa Balai Pustaka kini dialami oleh sastrawan generasi
cyber. Karya-karya mereka yang dimuat melalui internet diamini sebagai karya
yang instan.
Donny Anggoro (2008:198) mengatakan bahwa sastra cyber telah
lahir dan tidak bisa ditolak kehadirannya dalam kancah kesusasteraan Indonesia
modern. Menurutnya perdebatan-perdebatan yang muncul, apakah itu pro atau
kontra telah tercatat sebagai aksi sejarah munculnya media alternatif baru
penyaluran karya sastra via internet.
Sawali Tuhusetya (2007)
mengatakan bahwa melalui internet setiap orang bisa memublikasikan teks-teks
sastra ciptaannya, bahkan teks sastra yang tergolong ’sampah’ pun bisa dengan
mudah terpublikasikan. Hal yang hampir
mustahil terjadi dalam sastra koran. Untuk bisa meloloskan teks, sastranya di
sebuah media cetak, minimal harus lolos dari ’brikade’ selera sang redaktur.
Hal ini berarti bahwa tidak bisa sembarang teks sastra bisa lolos dari
persyaratan ketat yang ditetapkan oleh sang redaktur.
Suharjo (dalam Situmorang, 2004:63--64) mengomentari pendapat Maman S.
Mahayana. Ia mengatakan bahwa pendapat Maman tidak sepenuhnya keliru, karena
sebagian penyumbang naskah Graffiti
Gratitude itu tidak berpikir bahwa dirinya adalah penyair atau sastrawan. Mereka lebih senang dan nyaman dipanggil
sebagai penulis. Dalam hal ini ia mempertanyakan bilamana seorang dikatakan
sebagai sastrawan dan bilamana hanya disebut sebagai penulis saja. Ia mengutip pendapat William
Sloane yang mengatakan bahwa yang membuat sebuah buku menjadi karya sastra
adalah pembacanya, bukan kritikus sastra, editor, atau profesor. Selama karya
seorang penulis masih dinikmati, dibaca, didiskusikan dari waktu ke waktu maka
karya itu telah menjadi karya sastra dan
penulisnya menjadi sastrawan.
Rahman (2002:4) mempertanyakan apa itu sastra
majalah, sastra koran, dan sastra cyber? Pertanyaan ini tentu saja mengemuka karena muncul wacana yang mengatakan
bahwa sastra koran atau sastra majalah mutunya lebih baik daripada sastra cyber.
Dikatakan oleh Rahman bahwa menisbahkan sastra pada media, tempat karya sastra
disiarkan dapat dipastikan bertolak dari asumsi bahwa setiap media menentukan
corak dan kecenderungan karya sastra itu sendiri. Istilah sastra majalah,
koran, dan cyber bagi Rahman lebih sebagai ”politik identitas” dalam percaturan
wacana sastra. Istilah-istilah tersebut tidak pernah dirumuskan secara jelas,
kecuali sebagai pembeda belaka, dengan asumsi-asumsi yang dibangun di atas
karakter atau sifat setiap media. Oleh
karena itu, istilah-istilah tersebut
cenderung beroperasi dengan kesan, bahkan klaim subjektif, positif dan negatif,
tergantung pada posisi si pemberi klaim. Dengan demikian, Rahman mengatakan bahwa karya sastra yang baik adalah klaim yang
subjektif bukan kesimpulan yang ditarik dari pemeriksaan yang cermat, teliti,
dan seksama dalam sebuah bagan perbandingan.
Eksistensi
Sastra Cyber
Berdasarkan tanggapan atau komentar tentang sastra
cyber di atas dapat dilihat bahwa kehadiran sastra tersebut tidak semulus
sastra media cetak.Mengapa demikian? Hal ini dsebabkan kehadiran sastra cyber
tidak dengan serta merta diterima dengan baik. Bahkan, kehadirannya telah
menimbulkan polemik yang cukup ramai, seperti yang sudah diungkapkan di atas.
Misalnya, kalau kita cermati pendapat Ahmadun, tampak bahwa ia kurang simpatik
terhadap kehadiran sastra cyber. Hal ini tampak jelas dari perkataannya yang
mengatakan bahwa sastra cyber adalah sastra ’tong sampah’, ’sastra yang
memberontak terhadap kemapanan estetika’. Perkataan ini dapat dikatakan sebagai
perkataan yang kurang bijak dari seorang Ahmadun. Bagaimanapun juga sebagai
seorang senior yang sudah lama berkiprah di bidang sastra seharusnya ia bisa
lebih arif dan lebih bijak dalam menanggapi hal tersebut tanpa menyudutkannya.
Kalau kita
telusuri perjalanan sejarah sastra Indonesia, dapat dilihat di sana bahwa
selalu terjadi pemberontakan terhadap kemapanan. Misalnya, Chairil Anwar muncul
secara revolusioner. Ia memberontak terhadap kemapanan bentuk dan isi yang
terdapat pada puisi-puisi sebelumnya. Justru dengan pemberontakannnya terhadap
kemapanan tersebut ia dikenal dan dikenang sepanjang masa. Bahkan, hari
kelahirannya selalu diperingati dengan berbagai acara yang berkaitan dengan
sastra. Sutarji Coulsoum Bachri juga
muncul dengan kemuakan makna yang telah melekat pada kata. Ia mencoba
melepaskan makna dari kata. Bahkan, ia mempermainkan kata dengan seenaknya
sehingga pembaca banyak dibuat pusing untuk mengapresiasi karya-karyanya. Remi
Silado juga pernah memunculkan puisi-pusi ’mbeling’. Puisi-puisinya memberontak terhadap kemapanan dan
hegemoni para sastrawan senior. Dengan kata lain, selalu terjadi pemberontakan terhadap kemapanan. Sekarang
tinggal kita bagaimana menyikapi hal tersebut.
Apakah kita harus marah atau jengkel?
Bila berbicara soal media terbit, jelas ada pemerhati yang membedakannya, tetapi ada juga
yang tidak. Sastra yang diterbitkan melalui media cetak (sastra koran/majalah)
dikatakan lebih bermutu daripada sastra yang diterbitkan melalui media
elektronik. Hal ini disebabkan sastra koran hadir di hadapan pembaca melalui
prosedur dan seleksi yang ketat, sedangkan sastra cyber hadir sebaliknya.
Sastra cyber hadir tanpa prosedur yang ketat Oleh karena itu, siapa pun dapat
memublikasikan karya-karyanya secara leluasa untuk dinikmati oleh siapa saja
dari belahan dunia mana pun tanpa memandang apakah dia seorang yang sudah
dikenal atau seseorang yang namanya
belum dikenal. Kondisi ini menimbulkan
kegeraman bagi sebagian sastrawan yang sudah mapan, seperti yang terungkap
lewat pernyataan beberapa pelaku sastra
di atas. Kegeraman mereka sebenarnya tidak perlu terjadi jika mereka
bisa bersikap arif dan bijaksana. Apalagi perkembangan teknologi tidak bisa
dihindari, begitu juga sastra cyber yang lahir melaluinya. Ia sudah terlanjur
lahir, meskipun kelahirannya tidak disambut gembira oleh sebagian pelaku
sastra.
Sangatlah bijak jika Rahman mengatakan bahwa tidak perlu
memperdebatkan istilah yang berkaitan dengan sastra koran, sastra majalah, dan sastra
cyber. Baginya istilah-istilah itu sekadar ’politik identitas” dalam percaturan
sastra. Dengan demikian, tidak perlu muncul klaim-klaim yang bersifat subjektif.
Perlu juga dicermati pendapat William Sloan di atas bahwa yang membuat sebuah buku menjadi karya sastra
adalah pembacanya dan bukan kritikus, editor, atau profesor.Memang demikian
adanya bahwa karya sastra akan menjadi benda mati (artefak) tanpa peran
pembacanya. Karya sastra tidak akan berarti apa-apa tanpa campur tangan
pembacanya. Oleh karena itu, memang tidak perlu dipermasalahkan soal sastra
dari segi media karena hal tersebut justru akan menjadi sia-sia. Sastra cyber
sudah terlanjur lahir dan tentunya kehadirannya harus disambut dengan tangan
terbuka dan lapang dada.
Kemudian
dari segi tampilan, sastra terutama puisi juga berbeda. Jika dalam sastra koran
(puisi) hadir dengan deretan kata yang ditata sedemikian rupa, dalam puisi
cyber, kata-kata ditampilkan dengan
variasi yang bermacam-macam. Dalam arti, kata-kata bisa ditata sedemikian rupa,
seperti berloncatan, berlarian, dan berkejaran sehingga tampak menarik dan
indah. Keindahan itu semakin memukau ketika sastra tersebut diiringi dengan backsound dan background yang indah.
Sejarah Sastra Indonesia
Pada dasarnya sejarah sastra
adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan sastra dari
awal kemunculannya hingga sekarang. Karya-karya yang dapat masuk ke dalam sejarah sastra adalah karya-karya yang bermutu.
Tentu saja suatu karya dikatakan bermutu jika telah dinilai oleh seorang
kritikus atau orang yang ahli di bidang sastra. Penilaian terhadap sastra
tertulis, seperti yang terdapat pada
koran atau buku telah lama berlangsung. Hal ini telah dimulai sekitar tahun
20-an yaitu sejak adanya pengaruh Barat
di Indonesia.
Berbeda dengan sastra yang bermedia elektronik,
sastra ini baru dikenal sekitar tahun 2000-an. Usianya yang masih terlalu muda
tidak serta merta kehadirannya diterima
dengan tangan terbuka. Pro dan kontra pastilah bermunculan dengan kehadiran
sastra tersebut, seperti yang sudah dipaparkan di atas. Dikatakan oleh Semboja
(dalam Efendi, 2008:164) bahwa sejarah sastra Indonesia masih terbelenggu dalam
kanonisasi, masih tergantung pada kata pemegang otoritas. Apalagi sastra cyber
belum mempunyai etos yang mapan, seperti halnya sastra koran atau buku. Meski
usianya masih muda dan etos yang belum mapan, sastra cyber tetap bisa dikaji dan dinilai.
Dikatakan oleh Endraswara (2008:184)
bahwa untuk mengkaji sastra cyber ini sama dengan sastra yang bermedia koran
atau buku. Kita dapat menerapkan kode-kode seperti yang disampaikan oleh Teeuw
yaitu kode sastra, kode budaya, dan kode bahasa. Ketiga kode itu ternyata semua
ada dalam sastra cyber sehingga mau
tidak mau sastra tersebut harus mendapat perlakuan yang sama dengan sastra
lainnya. Dengan demikian, sastra cyber tidak pelu dianaktirikan dan ia harus
mendapat perhatian yang sama porsinya dengan sastra yang sudah mapan.
Bila dalam sastra yang sudah mapan dikenal sastra literer dan sastra
populer maka tidaklah menutup kemungkinan itu pun terdapat pada sastra cyber. Apalagi dalam jenis sastra ini siapa pun dari
kalangan mana pun dapat menuangkan perasaan maupun pikirannya melalui media
internet. Dengan demikian,
sastra cyber kalau diperlakukan sama dengan sastra yang sudah ada sebelumnya,
ia pun dapat dimasukkan ke dalam jajaran sejarah sastra Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, sudah siapkah para
peneliti sastra melakukan kajian terhadap sastra cyber, dan sudah siapkah para
sastrawan senior menerima kehadiran sastra cyber?
C. Simpulan
Sastra cyber merupakan sastra
yang kehadirannya di tengah-tengah kita masih terlalu muda. Namun, dengan
usianya yang masih terlalu muda tidak menutup kemungkinan untuk dilakukann
pengkajian terhadapnya. Memang sastra ini dapat dikatakan belum mempunyai etos
yang mapan seperti sastra yang ditulis dengan media yang lain. Pada awalnya,
media cetak satu-satunya alat untuk menuangkan segala ekspresi bagi sastrawan
dan memang tidak mudah bagi penulis pemula untuk memasukkan hasil karyanya
melalui media cetak. Banyak persyaratan
yang harus dilalui seseorang, sebelum dirinya disebut sebagai sastrawaan. Oleh karena itu, kehadiran sastra melaui internet menimbulkan kecemburuan
yang luar biasa bagi sastrawan senior. Betapa tidak? Karena untuk menulis di
media internet, tidak ada sensor yang ketat. Siapa pun dapat dan boleh
menuliskan apa saja. Tidak ada batas yang membatasi seseorang untuk
berekspresi.
Pada dasarnya sastra, apapun
medianya perlu mendapat perlakuan yang sama dari pemerhati sastra. Tidak perlu
ada ”penganaktirian” terhadap karya sastra karena hal ini akan menimbulkan
polemik yang tidak berkesudahan. Tindakan yang perlu kita lakukan saat ini adalah memperlakukan jenis karya sastra apapun
secara adil. Tidak perlu lagi membedakan antara sastra koran, sastrabuku atau
sastra elektronik. Semua jenis sastra ini pada dasarnya dapat masuk ke dalam
sejarah sastra dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan yang berlaku.
Daftar Rujukan
Endraswara,
Suwardi. 2008. Metodologi Penelitian
Sastra. Yogyakarta: MedPress.
Rahman,
Jamal D. 2002. ”Sastra, Majalah, Koran, Cyber”. Dalam Horison
Semboja, Asep.
2008. ”Peta Politik Sastra Indonesia (1908-2008)”. Dalam Anwar
Efendi (Ed.). Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Perspektif. Yogyakarta: Tiara
wacana.
Situmorang, Saut
(Ed.). 2004. Cyber Graffiti: Polemik
Sastra Cyberpunk. Bandung:
Angkasa.


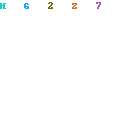

Tulisan yang bagus. Informatif. Terima kasih.
BalasHapus